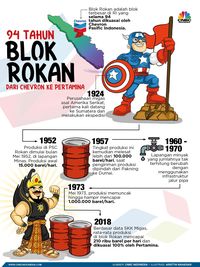Apa yang ada
di benak kita saat mendendangkan dua lagu yang sempat menjadi hits dari
John Lennon “Imagine” dan lagu dari REM yang berjudul “Losing My
Religion”? Beberapa pasti bakal menganggap bahwa kedua lagu tersebut
sebagai “berbahaya” namun mungkin pula ada sebagian menganggap kedua
lagu tersebut sebagai “baik-baik saja”. Mereka yang mengatakan bahwa
lagu “Imagine” berbahaya oleh sebab mereka merujuk pada beberapa kalimat
di dalam lagu tersebut yang menyiratkan gerakan anti-agama dan
serupa dengan lagu “Imagine”, lagu “Losing My Religion” juga bernada
serupa. Lalu darimana sebagian yang lain mengatakan bahwa kedua lagu
tersebut disebut sebagai “baik-baik saja”? Alasan mereka untuk menyebut
kedua lagu tersebut sebagai “bukan berbahaya” akan tetapi “baik-baik
saja” dilandasi oleh pemaknaan terhadap kedua lagu tersebut lewat
prosedur pemaknaan semiotika dan bukan literal. Secara umum, sebenarnya
apapun hasil pem-baca-an seorang pembaca baik literal maupun semiotik,
jika ditelaah lebih lanjut selalu merupakan suatu hasil dari penandaan.
Ini merupakan hal yang tidak bisa disangkal sebab bahasa sendiri adalah
media yang bersifat simbol. Jadi kedua pendapat sebenarnya bermain
dengan bahasa; kedua pendapat sebenarnya bermain semiotika.
Buchbinder
sendiri mengatakan bahwa pem-baca-an secara niscaya adalah suatu proses
memperlakukan suatu teks dengan cara-cara tertentu sehingga makna
diperoleh. Makna yang diperoleh inilah dapat disebut sebagai pesan yang
ada di dalam teks.
First,
there are the sets of relation and distinctive features common to all
utterances in the language; these are opposed in turn to an aspect that
may be called poetic. As Roman Jacobson said that the poetic function is
emphasize merely on for the message for its own sake (1991: 41).
kemudian ia melanjutkan bahwa:
The
reading of poetic texts then must first be seen in a correct relation
to the reading of more ordinary texts. Features such as rhyme,
rhythm, repetitions of words, phrases or images draw the reader’s
attention away from any reference to the context of reality (1991: 42.)
namun
apakah pem-baca-an semiotika meluputkan secara total sebuah karya
sastra terhadap dunia sesungguhnya? Jawabannya adalah tidaklah demikian.
Dunia sesungguhnya tetaplah cermin utama di dalam pemaknaan sebuah
karya sastra. Problem utama dari usaha naif untuk bersikap puritan di
dalam mem-baca dus memaknai sebuah karya adalah dengan memperlakukan
karya lepas dari induknya, yaitu: dunia, bahasa, pengarang. Semua karya
sastra memakai medium bahasa dan ketika ia terlahir ke dunia ia tentulah
dibuat: 1) karena ada dunia sebagai cerminnya, dan 2) mengikuti kaidah
konstruksi bahasa sebagai landasan eksistensi kebermaknaannya. Hal
demikian telah pula disinggung oleh Chandler sebagai berikut: “A
text is an assemblage of signs (such as words, images, sounds and/or
gestures) constructed (and interpreted) with reference to the
conventions associated with a genre and in a particular medium of
communication(2007: 5)” dan justru aspek linguistik bahasa-lah yang kemudian menjadi tumpuan atau jangkar (anchorage) bagi pemaknaan sebuah karya sebagaimana dikatakan oleh Barthes bahwa “Linguistic
elements can serve to ‘anchor’ (or constrain) the preferred readings of
an image: ‘to fix the floating chain of signifieds‘” (dalam Chandler, 2007: 204).
Mengapa tadi
dikatakan bahwa dunia, bahasa, pengarang ambil peranan di dalam
pem-baca-an suatu karya? Apakah dengan memasukkan pengarang ke dalam
sesuatu yang mencelupi pem-baca-an berarti makna yang dihasilkan berarti
menjadi sesuatu yang rigid? Atau dengan kata lain, jikalau pengarang
mengatakan bahwa karyanya memiliki arti A dengan demikian berarti kita
mengatakan bahwa tiada penafsiran lain terhadap karya tersebut yang sah
selain A? Tidaklah demikian. Sebab sebagaimana telah kita ketahui
bersama bahwa pem-baca-an merupakan suatu keadaan aktif memberikan makna
terhadap ruang-ruang kosong yang ada di dalam teks. Ia adalah keadaan
aktif mengkonstruk imaji dari apa yang tertulis di dalam teks
sebagaimana dikatakan oleh Iser (dalam Selden dkk., 1997: 50). Kondisi
ini juga dinyatakan oleh Gadamer (dalam Selden dkk., 1997: 54) sebagai
pengisian ruang kosong di dalam teks sebagai bentuk interaksi pembaca
dengan maksud pengarang yang berwujud teks.
Apa yang
dikatakan oleh Gadamer tidaklah sesederhana itu. Ia menambahkan bahwa
interaksi ini berlangsung dalam kondisi kekinian pembaca; bahwa apa yang
dilakukan pembaca di dalam membaca (atau mengisi ruang kosong)
berlangsung dalam taraf pengetahuan pembaca. Tidaklah mungkin pembaca
membuat tafsiran di luar pemahaman bahasa dan pengetahuan yang
dimilikinya pada saat proses pemaknaan berlangsung (dalam Abulad, 2007:
17-19 dan Palmer, 2005: 290-292).
Sehingga proses pembacaan adalah bisa
dikatakan sebagai “pembacaan bersama teks-teks lain” dan “pemaknaan
terkotori [atau terbantu?] oleh teks-teks yang dibaca sebelumnya” atau
Kristeva menggunakan istilah intertekstualitas teks (dalam Chandler,
2007: 197 dan Junus, 1985: 87-88). Perlu digarisbawahi bahwa
“pengetahuan tentang pengarang” oleh pembaca tidak bisa dilepaskan dari
penafsiran semiotika meskipun pembacaan semiotika bukanlah pembacaan
dalam rangka mencari makna yang dimaksudkan oleh pengarang. Sebab
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemaknaan adalah bersifat
kekinian pembaca (Gadamer Selden dkk., 1997: 54) dan pemaknaan telah
ditakdirkan bukanlah pekerjaan untuk menyamakan makna yang kita peroleh
dengan makna yang dimaksudkan pengarang (Barthes, 1977). Sebab merujuk
kepada apa yang dikatakan oleh Kristeva dan juga Gadamer, pem-baca-an
berlangsung bersama teks-teks lain dan pada akhirnya akan menghasilkan
produk kondensasi berupa “kompromi” simbol dan makna; atau berupa fusi
horizon pembaca dengan pembuat teks.
Ok, dapatlah
dimahfumi hal demikian. Namun bersandar kepada apa yang telah kita
bicarakan di paragraf awal tulisan ini, keadaannya tidaklah segampang
itu. Bagaimana jika pembaca BAHKAN ketika sudah mendapatkan kondensasi
simbol dan makna sebenarnya masih dihantui oleh sesuatu yang telah
pernah ia sengaja tidak ambil? Bagaimana jika semesta simbol dan makna
yang telah ia pilih ternyata masih dibayang-bayangi oleh alusi yang
lain? Pemikiran demikian dimuntahkan oleh Derrida (dalam Belsey, 2001:
116) untuk menunjukkan bahwa pemaknaan adalah sebuah permainan yang tak
pernah usai dimainkan. Sebenarnya Gadamer sudah menyinggung tentang hal
itu. Kedinamisan bahasa dan semesta makna membuat pemaknaan yang tetap
musykil terjadi. Pem-baca-an dan tafsir selalu bersifat kekinian
sedangkan simbol-makna lain sebenarnya tidak pernah terhapus namun hanya
tercoret saja karena “itu” masih tetap di sana; bersama dengan
pemaknaan yang telah kita buat dan “itu” bisa saja secara radikal
menyeruak menggugat dan lalu menggantikan makna yang sebelumnya telah jadi.
Kembali kepada dua lagu yang kita bahas di dalam tulisan ini, Imagine dan Losing My Religion memberikan “tantangan” bagi pem-baca-an serius. Jika kita baca lirik Imagine maka
beberapa baris akan memberi permainan penentuan makna [sementara].
Ketika seorang pembaca berhadapan dengan dua baris pertama lagu ini,
Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try
No hell below us, above it’s only sky
ia bisa saja
mengatakan bahwa lagu ini tidaklah menggugat agama, lagu ini adalah
lagu yang mengkritik bagaimana orang-orang yang beragama menyalahgunakan
agama untuk mengklaim langit mendukung mereka padahal sebenarnya nafsu
keserakahan ada di dalam hati mereka. Mungkin jika menyinggung ini,
seorang pembaca ada kemungkinan akan membayang pikiran pada satu baris
dari Counting Crows dalam lagu Big Yellow Taxi: “They paved paradise to put up a parking lot“. Bayangan pembaca bahwa lagu ini bukan tentang memusuhi agama semakin diperkuat mungkin dengan kata pertama imagine dan baris penutup bait pertama dari lagu ini adalah “imagine all the people, living for today“. Pembaca dapat saja mengatakan bahwa kata kuncinya adalah living for today.
Jadi dia mendapatkan dua hal dari baris ini: 1) bahwa lagu ini hanya
sebuah perumpamaan, dan 2) lagu ini menggugat keadaan terkini, saat
orang-orang menggunakan agama sebagai topeng atas keserakahan.
NAMUN
pembaca tersebut bisa saja di dalam pem-baca-annya merasa
terbayang-bayangi oleh apa yang telah dinyatakan oleh John Lennon,
penulis lagu Imagine, bahwa:
“But
the song ‘Imagine,’ which says, Imagine that there was no more
religion, no more country, no more politics is virtually the communist
manifesto, even though I am not particularly a communist and I do not
belong to any movement. You see, ‘Imagine’ was exactly the same message,
but sugar-coated. Now ‘Imagine’ is a big hit almost everywhere;
anti-religious, anti-nationalistic, anti-conventional, anti-capitalistic
song, but because it is sugar-coated it is accepted. Now I understand
what you have to do” – John Lennon
Bilamana
pem-baca-an berlangsung dalam keadaan demikian [mengetahui dunia,
bahasa, dan pengarang [dus intensi penciptaan suatu karya]], seorang
pembaca pastilah harus mencoret salah satu bagian dari semesta simbol
dan makna yang tersedia bagi pem-baca-annya dan berkata bahwa “ini”
adalah makna dari teks ini. Momen seorang pembaca MENENTUKAN bahwa lagu
tersebut “hanya perumpamaan” dan “sindiran terhadap penyalahgunaan
agama” serta “bukan anti agama” dus “ajaran atheis-komunis” selalu
terbayang-bayangi oleh kemungkinan penjungkalan radikal oleh makna lain
yang tadinya dicoret bahwa “ya, lagu ini sebenarnya adalah lagu
provokasi anti-agama”.
Lalu apa kaitan lagu ini dengan lagu dari REM, Losing My Religion? Meskipun lagu dengan lirik seperti ini:
Life is bigger
It’s bigger than you
And you are not me
dan kemudian di bait lain:
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don’t know if I can do it
Oh no I’ve said too much
dikatakan
BUKAN tentang seseorang yang “sudah tidak percaya lagi akan iman” atau
“hilang kepercayaan terhadap Tuhan” oleh sebab dikatakan bahwa ungkapan “losing my religion”
adalah sebuah ungkapan orang Amerika Serikat daerah Selatan yang
artinya: “sudah tidak percaya lagi kepada seseorang” dan bahkan band REM
juga menyatakan demikian, akan tetapi generasi simbol dan makna yang
ditimbulkan lirik dan video klip lagu ini dapat menegasikan pernyataan
band REM bahwa lagu ini bukan tentang “hilang kepercayaan terhadap
Tuhan”.
Pembaca [atau dalam konteks ini, penikmat musik] lagu Losing My Religion tidaklah bisa untuk menghapus kemungkinan pem-baca-an lain bahwa lagu ini MUNGKIN memang tentang “hilang iman” sebab arti religion memang agama.
Saat seorang penikmat lagu [atau pembaca lirik] berada di dalam momen
menentukan bahwa lagu ini adalah tentang “cinta bertepuk sebelah tangan
atau unrequited love” ia bakal selalu dibayang-bayangi oleh
simbol atau makna lain yang ia coret (namun masih kelihatan; bukan
dihapus) atau ia hilangkan (meskipun bayangan itu selalu potensial untuk
kembali) bahwa “ya, lagu ini sebenarnya adalah tentang hilang iman”.
Jadi sampai di manakah kita? Apakah kita lantas menjadi pembaca yang
tidak mau menentukan makna ataukah memang kata-simbol-makna adalah hal
yang rapuh sebagaimana ungkapan dari Derrida bahwa menentukan sesuatu
adalah keterpaksaan oleh keadaan saat itu yang bisa jadi terasa “inadequate yet necessary” sebab kita terus bergerak meskipun dalam bayang-bayang terdekonstruksi oleh, justru, diri kita sendiri.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1255525/original/058088900_1465178780-IMG_20160605_163940.jpg)